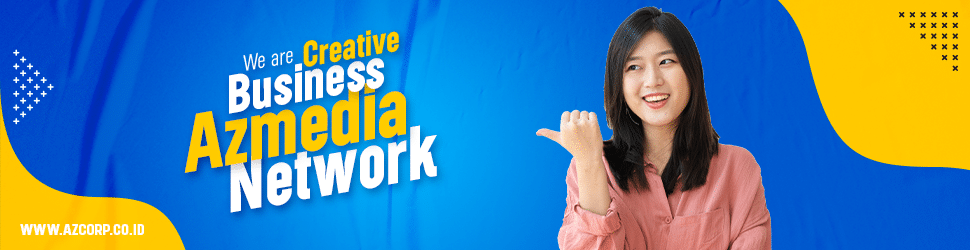Tulungagung, AZMEDIA INDONESIA – Peristiwa keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, sejatinya bukan sekadar fragmen tragis dari kegagalan dapur kolektif. Ia adalah manifestasi ontologis dari konflik laten antara logika kesejahteraan publik dan naluri akumulasi kapital. Di atas piring nasi anak-anak sekolah, hukum pidana modern diuji bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai realitas kekuasaan yang hidup—atau justru mati—dalam praktik sosial.
Dalam horizon epistemologis hukum pidana kontemporer, pengetahuan tidak lagi dibangun semata dari intensi subjektif pelaku, melainkan dari relasi kausal objektif antara tindakan korporasi dan akibat sosialnya. “Aroma basi” pada lauk yang dikonsumsi siswa bukan sekadar pengalaman inderawi, melainkan fakta empiris yang menegaskan kegagalan sistemik pengendalian risiko.
Di sinilah prinsip pertanggungjawaban mutlak menemukan relevansinya sebagai metode berpikir hukum modern: kesalahan tidak disimpulkan dari kehendak jahat, tetapi dari kegagalan struktural mencegah bahaya yang secara rasional dapat diperkirakan. Epistemologi ini menolak romantisme niat baik korporasi dan menggantikannya dengan logika objektivitas risiko. Dalam dunia pangan publik, bahaya yang terwujud adalah bukti kesalahan itu sendiri.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara psikologi sosial, korporasi bukan entitas netral, melainkan organisme ekonomi dengan dorongan dasar: efisiensi biaya dan maksimalisasi surplus. Naluri ini, ketika tidak dikekang norma, melahirkan rasionalisasi berbahaya—bahwa kualitas dapat dikompromikan, bahwa risiko kesehatan adalah variabel yang bisa “diterima”.
Di titik inilah kelalaian berhenti menjadi kecelakaan dan bertransformasi menjadi kebijakan diam-diam. Penghematan bahan baku, longgarnya kontrol mutu, dan formalitas pengawasan adalah ekspresi fisiologis dari kekuasaan ekonomi yang menganggap tubuh publik sebagai ruang eksperimen profit. Anak-anak sekolah, dalam logika ini, direduksi menjadi statistik biaya.
KUHP Nasional (UU 1/2023) menandai pergeseran ontologis mendasar: korporasi tidak lagi sekadar fiksi hukum administratif, tetapi subjek pidana dengan kapasitas bersalah. Pasal 48 menegaskan tindak pidana dalam lingkup usaha sebagai tindak pidana korporasi; Pasal 49 mengikat pengurus yang gagal mencegah.
Ontologi baru ini menolak ilusi bahwa kejahatan modern selalu bertangan manusia individual. Ia mengakui bahwa dalam kapitalisme organisasi, keputusan kriminal sering lahir dari struktur, prosedur, dan kebijakan—bukan dari impuls personal semata. Bungur, dalam konteks ini, adalah contoh konkret bagaimana bahaya diproduksi oleh sistem.
Pertanggungjawaban mutlak bukan anomali, melainkan konsekuensi rasional dari kompleksitas risiko modern. Rasio legis-nya jelas: perlindungan publik dalam sektor berbahaya tidak boleh bergantung pada pembuktian niat yang nyaris mustahil dalam struktur korporasi.
Hukum mengalihkan beban kehati-hatian sepenuhnya kepada pelaku usaha. Siapa mengelola pangan publik, menanggung seluruh risiko bahaya yang timbul. Negara, melalui norma ini, menyatakan satu hal sederhana namun radikal: keuntungan tidak boleh dibangun di atas probabilitas penderitaan masyarakat.
Dalam dimensi praksis, pembuktian pidana korporasi tidak cukup dengan kesaksian korban. KUHAP menyediakan instrumen epistemologis yang lebih dalam: alat bukti surat sebagai jejak material kehendak ekonomi.
Buku kas, nota pembelian, kontrak pemasok, serta catatan distribusi adalah arsip moral kapitalisme. Dari sanalah terbaca apakah kualitas dikorbankan demi margin laba. Selisih harga yang tidak wajar, bahan baku bermutu rendah, atau laporan manipulatif bukan sekadar pelanggaran administrasi—ia adalah narasi konkret dari pilihan sadar yang memproduksi bahaya.
Sejarah penegakan hukum Indonesia sarat ironi: buruh kecil dihukum, struktur besar lolos. Juru masak dipenjara, pengusaha tetap beroperasi. Padahal hukum pidana korporasi lahir justru untuk meruntuhkan ilusi ini.
Menghentikan perkara di level pekerja lapangan adalah bentuk pengkhianatan ontologis terhadap semangat KUHP baru. Itu mengembalikan hukum ke era individualistik yang buta terhadap realitas kekuasaan ekonomi modern.
Kasus Bungur bukan hanya soal 24 siswa yang sakit; ia adalah cermin apakah negara hukum Indonesia sungguh berani menundukkan kapital pada norma, atau masih tunduk pada kekuatan modal.
Secara epistemologis, fakta telah cukup. Secara ontologis, subjek pidana telah jelas. Secara rasio legis, tujuan hukum terang: perlindungan publik melalui tanggung jawab mutlak.
Yang tersisa hanyalah keberanian politik-penegakan hukum.
Sebab di titik ini, membiarkan korporasi lolos bukan sekadar kegagalan prosedural—melainkan pernyataan sunyi bahwa kesehatan anak-anak masih kalah nilainya dibanding neraca laba. Dan di sanalah hukum berhenti menjadi peradaban, berubah menjadi dekorasi kekuasaan.